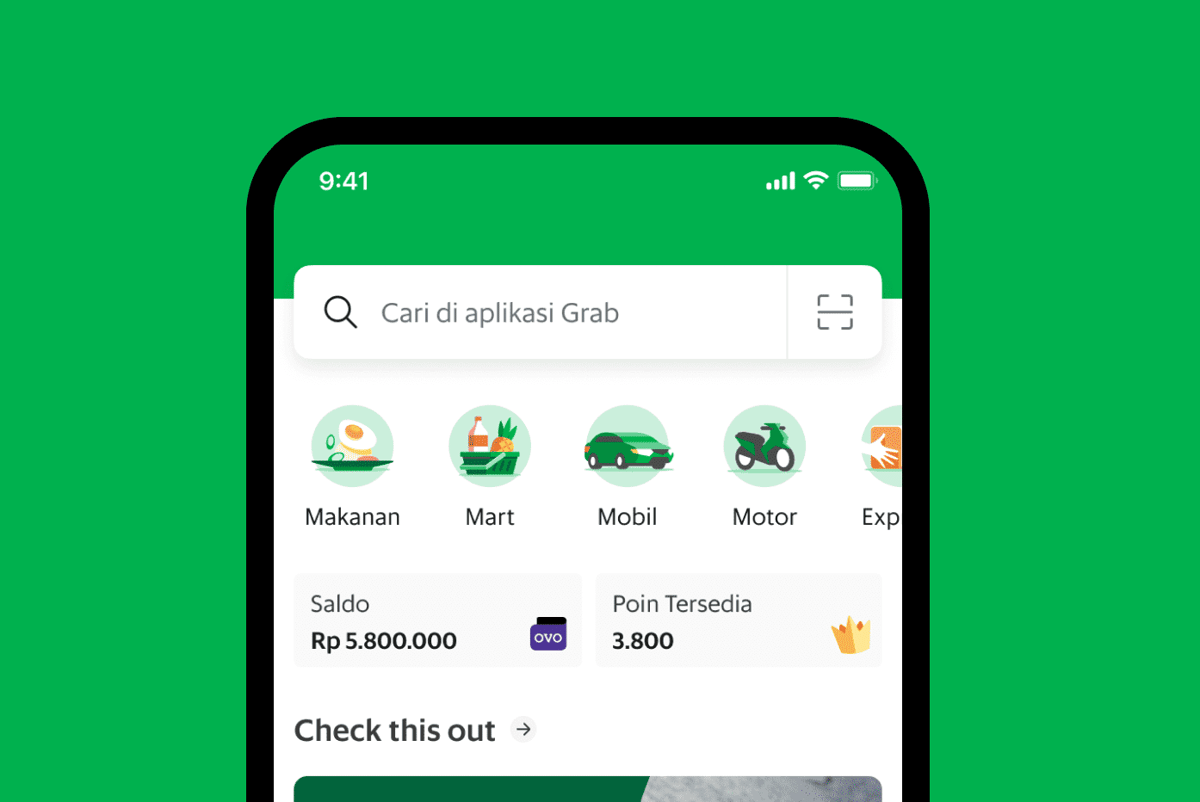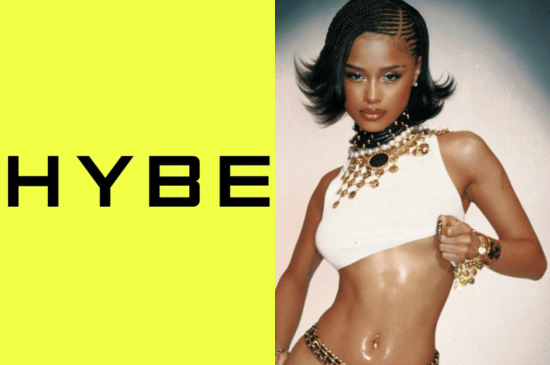'Ali & Ratu Ratu Queens', Kisah dari New York yang Hangatkan Hati

Bagai ranting patah, yang kemudian digunakan untuk menyalakan perapian demi hangatkan ruangan. Seperti itulah rasanya ketika menyaksikan Ali yang sempat tak diakui anak oleh Mia, mamanya. Namun, seperti api tadi yang perlahan mulai menebar kehangatannya, hati saya seolah ikut menghangat saat kemudian Ali diterima oleh sekelompok perempuan berusia dewasa yang dikumpulkan oleh keadaan. Turut bahagia dan haru rasanya ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang selalu ada di sisi kita dalam keadaan apapun. Baik saat sulit, maupun suka.
Rasa hangat itu bahkan masih saya rasakan saat menulis review singkat tentang Ali & Ratu Ratu Queens ini. Serasa saya pun ingin memiliki keluarga sehangat Ance, Biyah, Party dan Chinta.

Ali (Iqbaal Ramadhan) memutuskan untuk ke New York setelah tiga bulan meninggalnya sang ayah, untuk mencari ibunya, Mia (Marissa Anita). Mia meninggalkan Ali dan suaminya di Indonesia untuk mengejar mimpinya di kota impiannya, New York.
Dengan uang hasil sewa rumah orangtuanya, Ali nekat ke New York berbekal alamat dari surat yang pernah dikirimkan Mia. Setibanya di New York, Ali tak menemukan Mia. Ia malah bertemu dengan empat perempuan seusia sang mama yang menerimanya dengan tangan terbuka. Mereka adalah Party (Nirina Zubir), Chinta (Happy Salma), Biyah (Asri Welas), dan Ance (Tika Panggabean).
Empat perempuan tersebut berhasil mendapatkan alamat baru Mia. Sayangnya, sambutan Mia terhadap Ali yang sudah jauh-jauh menyusulnya ke New York tak sesuai dengan harapan Ali.

Ekspektasi saya terhadap gemerlapnya New York yang mungkin akan ditampilkan dalam film ini mendadak sirna. Sebab, lewat arahan jeniusnya, sang sutradara Lucky Kuswandi berhasil menghadirkan New York dengan perspektif berbeda.
Kita dibawa ke sisi sederhana Kota New York yang membuat penonton mungkin berpikir bahwa semua orang bisa datang ke kota megapolitan tersebut tanpa harus menunggu ‘sukses’.
“Ini New York. Kamu tak perlu khawatir. Uang gampang dicari di sini.” Kutipan dari Ance ini saya garis bawahi dan semakin membuat saya percaya, bahwa di balik sisi gemerlap New York yang serba cepat dan individual, tersimpan kesederhanaan sekaligus kekuatan bagi mereka agar tidak takut untuk menjelajah hal baru. Termasuk ke New York.

Untuk soal cerita, sekali lagi saya harus angkat topi untuk Gina S. Noer. Kisah yang ditulis dengan konflik yang jelas, kompleks, namun mengalir tanpa ada bagian yang ‘patah’ membuat saya terpaku sejak menit pertama diputar.
Sama seperti film keluarga lainnya yang sukses ditulis Gina (Keluarga Cemara dan Kulari Ke Pantai), sosok Ali berkembang secara perlahan menuju proses pendewasaan diri dan ‘meledak’ sebagai pertanda bahwa kita berada di puncak konfliknya.
Perjalanan Ali semakin terasa nyata dan membuat saya hanyut karena diiringi oleh deretan soundtrack yang tak hanya familiar, tapi juga sangat menggambarkan New York. “Khayalan” oleh The Groove, “Location Unknown” oleh Honne, “Why Would I Be” oleh Teddy Adhitya, dan “Sisa Hari” dari Ify Alyssa, sukses menambah warna pada New York dalam film itu.

Satu hal yang saya dapatkan dari kisah ini adalah, keluarga bisa hadir bukan hanya dari ikatan darah. Lebih dari itu, pada kenyataannya, keluarga juga bisa terbentuk karena suatu keadaan yang sama. Saling mendukung satu sama lain, menguatkan di saat sulit, hadir di saat bahagia dan tak pernah menghakimi jika berbuat salah, adalah definisi keluarga yang sesungguhnya.