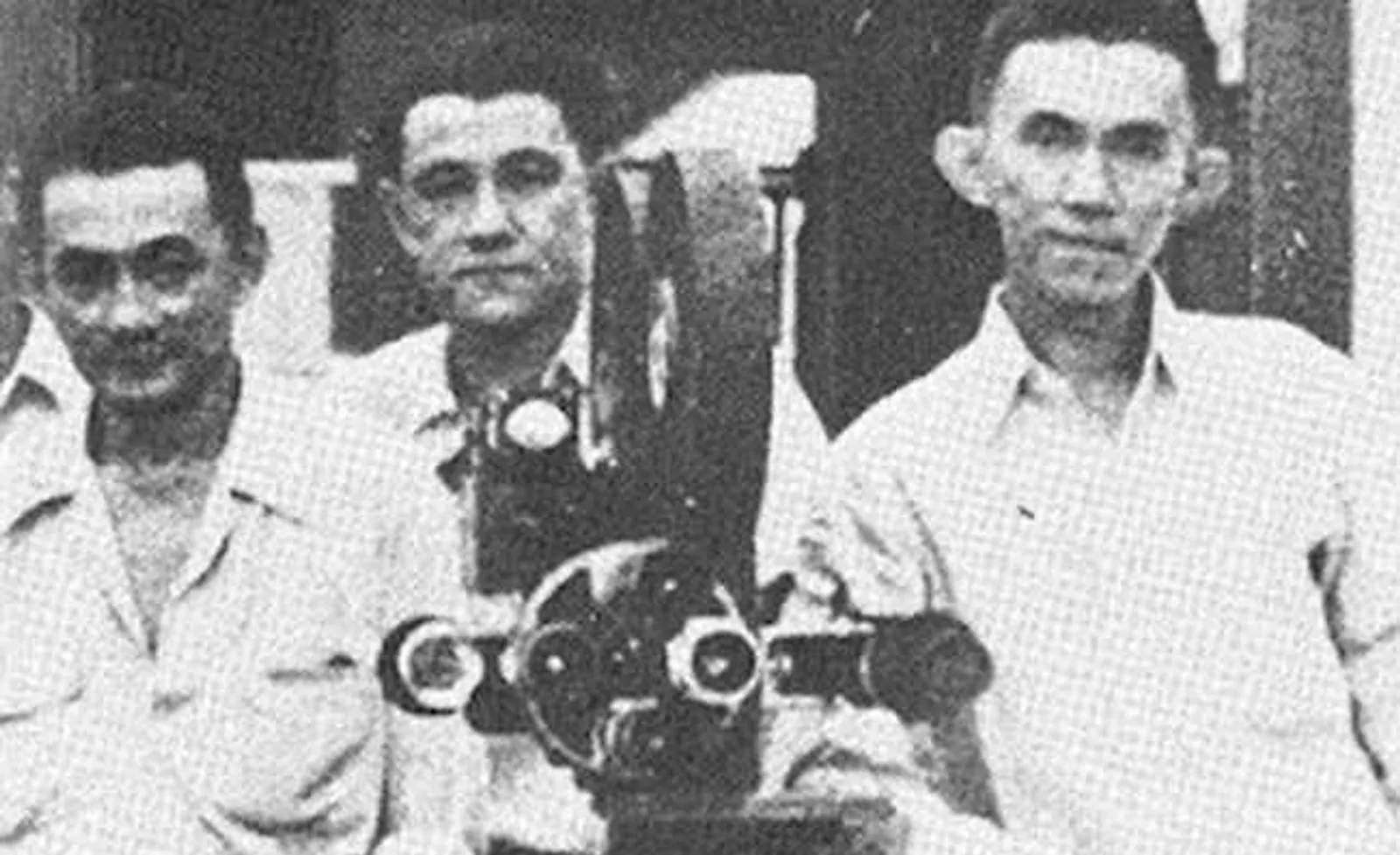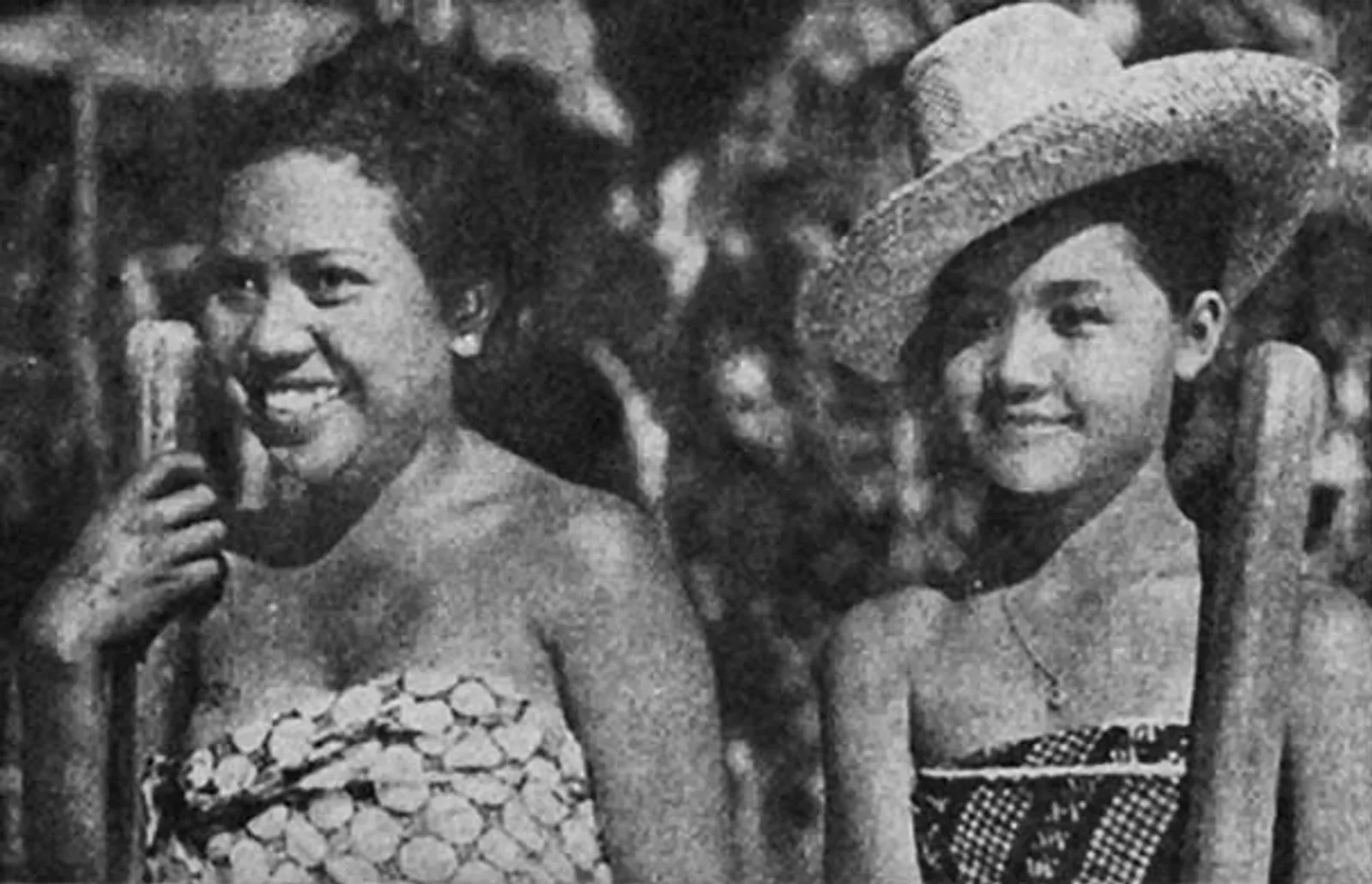Semua orang membutuhkan hiburan untuk keluar sesaat dari rutinitas yang melelahkan atau membosankan. Menurut American Psychology Association, kecenderungan tersebut merupakan bagian dari escapism theory yang umumnya dialami oleh setiap individu.
Nah, biasanya, film kerap dijadikan sebagai salah satu opsi dari metode escapism dalam ilmu psikologi. Good news! Dalam rangka merayakan Hari Film Nasional yang jatuh pada hari ini, 30 Maret, Popbela menyediakan rekomendasi film nasional dari tahun ke tahun, nih!
Namun, ada yang berbeda! Di sini, kamu akan turut menjelajahi sejarah panjang perfilman Indonesia dan mengintip beberapa rekomendasi judul film pada masing-masing era. Apakah kamu cukup antusias dan penasaran? Let's travel the history!
1920-1930: pengaruh Tionghoa yang mendominasi
Tahukah kamu? Film nasional nyatanya telah berdiri jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya sendiri. Sehingga, cukup wajar jika film nasional saat itu dibayangkan sebagai produk adiluhung yang steril dari nilai-nilai yang mencerminkan bangsa Indonesia.
Dengan kata lain, produksi film-film pada masa itu cenderung terpaut pada tujuan hiburan semata dengan sentuhan dari budaya negara-negara asing. Khususnya pengaruh Tionghoa yang dianggap memperkenalkan modus produksi film-film hiburan eskapis.
Meski begitu, film Indonesia tetap dapat cukup berbangga atas produksi film yang berhasil ditayangkan. Sebut saja, Loetoeng Kasaroeng (1926) dengan konsep bisu yang sukses ditayangkan untuk pertama kalinya di teater Elite and Majestic di Bandung.
Melihat kesuksesan yang diterima, pembuatan film lokal pun mencoba peruntungan baru dengan konsep film bicara atau menggunakan dialog. Di antaranya adalah Botenga Roos (1931) hingga Indonesia Malaise (1931) yang diketahui memperoleh kritik yang negatif.
1930-1940-an: perpaduan budaya Tionghoa dan Belanda
Memasuki dekade 1930-an hingga 1940-an, industri perfilman Indonesia masih belum lepas dari pengaruh budaya asing. Kali ini, Indonesia mengalami masa-masa ketika citra visual Indonesia turut digambarkan dari sudut pandang yang dirumuskan oleh Belanda.
Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengaruh Tionghoa masih berlaku. Sehingga karakteristik film-film nasional pada era tersebut dapat dikatakan seperti memadukan gaya film Shanghai dengan film-film western layaknya Hollywood yang sudah populer.
Meski begitu, cerita-cerita lokal yang diangkat bersifat lokal dengan karakteristik mempertemukan narasi-narasi dari berbagai belahan Indonesia. Begitu juga dengan potret warga nusantara yang digambarkan dengan perpaduan kesan kosmopolitan dan hibrida.
Sebut saja, film Pareh yang diperkiran tayang pada sekitar 1934-1936. Secara garis besar, film ini memang mengenai keindahan Hindia-Belanda. Namun, pada kenyataannya, ia merupakan hasil kerja sama antara Albert Balink dan Mannus Franken dari Belanda dan industri film Shanghai bernama Wong bersaudara.
Nah, selain judul film tersebut, beberapa film yang memiliki sentuhan serupa adalah Tjonat (1930), Terang Boelan (1937), dan Roentjong Atjeh (1940) yang populer di era tersebut.
1942-1949: propaganda Politik Jepang
Sebelum benar-benar memasuki masa Kemerdekaan Indonesia, negara penjajah Jepang nyatanya masih berupaya untuk meruntuhkan fondasi persatuan Indonesia. Salah satu cara adalah, dengan memanfaatkan film nasional karena mendapat perhatian publik.
Yup, melalui cara tersebut, Jepang secara spesifik menggunakan film nasional Indonesia sebagai alat propaganda Politik Jepang. Dampaknya, produksi film Indonesia yang tengah dikembangkan mulai mengalami masa kesurutan yang cukup signifikan.
Bagaimana tidak! Film 'propaganda' menyebabkan penyesatan ideologi yang membuat masyarakat terpecah ke dalam beberapa kelompok akibat perdebatan. Atas dasar itulah, tudingan terhadap film nasional dilontarkan sebagai upaya untuk menghentikan perkembangannya.
Melihat masalah tersebut, Usmar Ismail yang dikenal sebagai Bapak Perfilman Nasional melakukan upaya solutif yaitu, mengembangkan panggung 'Sandiwara' sebagai pengganti bioskop dan menarik para artis atau pelaku seni untuk berkarya di sana.
1950-an: upaya tetap mempertahankan perfilman nasional
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Indonesia memang dapat dikatakan mengalami masa keruntuhan di bidang perfilman nasional. Meski begitu, Bapak Perfilman Nasional Usmar Ismail terbilang cukup pantang menyerah untuk menerima kenyataan pahit.
Selain membangun panggung 'Sandiwara' sebagai opsi pengganti bioskop, beliau tetap berupaya menyutradarai sebuah film yang dikenal dengan judul Darah & Doa atau Long March of Silliwangi (1950), dengan pengambilan gambar pertama pada 20 Maret 1950.
Dari situ, Usmar Ismail secara tidak langsung menginspirasi negara untuk tetap mengupayakan kemajuan industri perfilman nasional. Terbukti dari peresmian bioskop termegah dan terbesar pada era tersebut yang dikenal dengan nama Metropole.
1960-an: aksi pemboikotan film-film di bioskop
Dengan upaya mempertahankan eksistensi perfilman nasional, apakah ditemukan tanda-tanda positif terkait perkembangan film-film di Indonesia? Tentu tidak! Pasalnya, jejak penilaian yang dianggap tidak sesuai, masih membekas di kalangan masyarakat.
Terlebih lagi, isu terkait G 30S PKI berkembang pada era 1960-an sehingga menyebabkan peredaran film nasional kian rusak. Akan tetapi, perfilman Indonesia tetap mendapat bantuan dari film-film impor yang masuk dan berupaya meningkatkan jumlah penonton.
Sayangnya, seiring berjalannya waktu, sebagian besar film impor dinilai bersifat imperialis Amerika dan hal itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat saat itu. Akibatnya, pada sekitar 1964-1965, aksi pemboikotan film-film impor di bioskop-bioskop pun terjadi.
1990-an-2000-an: masa kebangkitan film nasional
Indonesia telah cukup lama mengalami masa kesurutan di bidang perfilman nasional, yang bukan lain disebabkan oleh campur tangan negara asing serta ketidakcocokan masyarakat terhadap nilai-nilai yang dihadirkan. Namun, masa pemulihan pun akhirnya mulai terjadi.
Memasuki tahun 1990-an, industri perfilman nasional mulai kembali mencoba peruntungan baru. Pada awalnya, hasil yang diperoleh tidak dapat dikatakan baik secara signifikan akibat pesatnya perkembangan telivisi swasta, VCD, LD, dan DVD yang menyaingi eksistensi film.
Oleh karena itulah, percobaan yang dilakukan oleh industri perfilman Indonesia fokus pada produksi dua hingga tiga film saja setiap tahunnya. Namun, siapa yang menyangka bahwa proses yang terlihat minim mampu menarik perhatian masyarat secara perlahan juga!
Sebut saja keberhasilan Cinta dalam Sepotong Roti (1991), Petualangan Sherina (2000), dan Ada Apa dengan Cinta? (2000). Melalui film-film inilah, Indonesia dapat dikatakan mulai mengalami masa kebangkitan di bidang perfilman nasional
2010-sekarang: mendobrak kancah internasional
Berhasil memasuki masa kebangkitan, perfilman Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas yang kian terbukti. Bukan hanya di tingkat nasional, namun internasional. Sebut saja, The Raid (2011) yang mendapat kritik positif dari berbagai negara di belahan dunia.
Dari situ, masyarakat pun sudah mulai dapat menghitung beberapa nama aktor maupun aktris yang memperoleh perhatian global. Sebut saja, Joe Taslim yang terlibat dalam film berbasis internasional seperti, Fast & Furious 6 (2013) dan The Swordsman (2020).
Begitu juga beberapa nama pelaku film lainnya, seperti Iko Uwais yang terlibat dalam Man of Tai Chi (2013), Star Wars: The Force Awakens (2015), hingga Mile 22 (2018). Begitu juga Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian yang tampil spektakuler dalam John Wick 3 (2019).
So, sekarang, kamu telah melihat sejarah panjang perfilman Indonesia, berikut dengan judul-judul film yang direkomendasikan. Kira-kira kamu akan mulai menonton film nasional yang mana, nih? Atau ada film nasional terbaru yang sangat menarik perhatianmu?